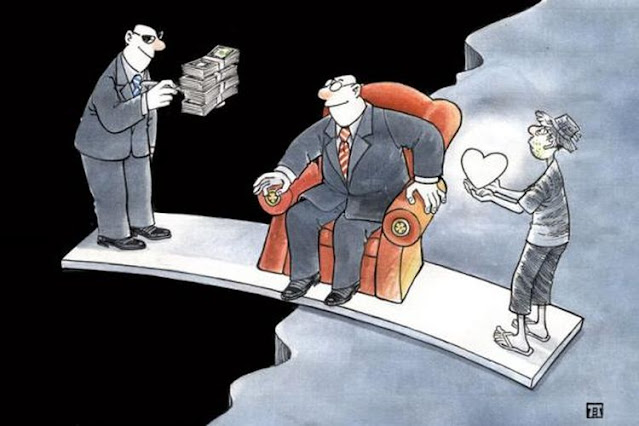Beragama Dengan Kesadaran; Dari Akal ke Spiritual
Oleh : Teuku
Muhammad Jafar Sulaiman dan Zuhri Sabri
Pada umumnya setiap orang yang beriman kepada agama
(Tuhan) mengakui akan pentingnya makna beragama dengan kesadaran sebagai
konsekuensi dari keimanan yang dimilikinya. Namun bukan berarti seluruhnya juga
memiliki kandungan pemaknaan yang sama tentang hal ini. Sebagian dari konsep iman
itu memperkenalkan keimanan strukturalis, yang mensyaratkan adanya kebutuhan
mutlak terhadap suatu struktur institusi tertentu yang dapat mengorganisir
penganut agama agar taat dan patuh pada perintah dan larangan agama. Dengan
kata lain makna beragama dengan kesadaran menurut konsep ini diwujudkan melalui
institusi hukum sebagai sarana paling otoritatif yang menghubungkan antara
manusia dan khaliknya.
Setiap orang pasti memiliki kesadaran terhadap realitas
yang terkait dengan kehidupannya. Salah satu kesadaran yang paling mendasar
bagi manusia adalah kesadaran bahwa dirinya hidup dan oleh karenanya
berkeinginan untuk mempertahankan kehidupannya. Kesadaran dasar ini pada
tahapan berikutnya akan menstimulasi sejumlah aktifitas, tindakan dan pemikiran
yang bertujuan untuk melindungi, memberikan kenyamanan dan sekaligus keinginan
untuk memajukan kualitas kehidupannya secara lebih sempurna.
Dalam mewujudkan keinginan-keinginan dasar kemanusiaan
itu, agama muncul sebagai salah satu pilar yang diyakini banyak ummat manusia
sebagai institusi yang mampu menjamin terpenuhinya keinginan dasar tersebut,
karena agama mengandung nilai-nilai dasar yang bersumber dari yang Maha Benar,
sehingga dengan mengikuti seluruh pesan agama pasti dapat mengarahkan hidup
manusia kearah yang benar. Atas dasar ini semestinya kesadaran kemanusiaan
menjadi makna esensial dari makna “beragama dengan kesadaran”.
 |
| Sumber : Google |
Salah satu nilai khas cara kerja hukum yang membedakannya
dengan norma sosial lainnya yakni adanya daya paksa, kemampuan mengidentifikasi
kesalahan/kejahatan secara kongkrit (positif) dan memiliki hukuman sebagai konsekuensi
dari pelannggaran norma hukum tersebut. Elemen identifikasi terhadap sesuatu
yang kongkrit dalam hukum
meniscayakan adanya sesuatu yang dapat diukur, memiliki sistem dan mekanisme
validasi yang mapan.
Beragama
dengan Kesadaran
Namun apakah Iman juga dapat masuk dalam kategori yang
demikian?. Jika merujuk pada ketentuan yang demikian maka kita juga harus
memiliki alat ukur yang namanya Iman, alat ukur ketaqwaan, dosa serta
elemen-elemen keagamaan lainnya, tapi apakah hukum juga mampu merambah pada
pengukuran yang demikian?. Pandangan umum yang lazim diyakini menurut konsep
ini adalah terjadinya kepatuhan massal terhadap hukum-hukum agama yang
diorganisir oleh Negara melalui daya paksa Hukum telah mencerminkan keimanan dan ketaqwaan
ummat beragama. Analogi yang sering diperkenalkan adalah jika seseorang ingin
menjadi anggota kepolisian maka ia harus tunduk dan patuh pada sistem latihan
calon anggota polisi yang diterapkan oleh instruktur atau pelatih, sehingga
kelak akan menjadi polisi yang professional dalam memperagakan keahlian
dibidang kepolisian. Namun apakah kemampuan seorang polisi dalam memperagakan
keahlian dalam bidang kepolisian tersebut secara otomatis mencerminkan bahwa ia
telah menjadi seorang abdi Negara yang ideal? Tentu saja belum bisa dipastikan
demikian, buktinya hingga saat ini dimanapun juga, tetap saja ada oknum
kepolisian yang justru memboncengi kejahatan dan bahkan pelaku kejahatan itu
sendiri. Artinya keahlian seorang polisi dalam ilmu kepolisian tidak bisa
menjadikan sandaran absolut bahwa ia adalah seorang yang baik, dan tulus
mengabdi pada Negara.
Demikian juga dalam hubungan hukum dan keimanan dalam
agama, hukum tidak memiliki kapasitas untuk menilai baik buruknya keimanan
seseorang, bahwa seseorang taat secara hukum agama belum memastikan ia seorang
beriman, hal ini bisa disaksikan dari masih banyak orang tersakiti atas nama
agama, banyak tragedi kemanusiaan di berbagai belahan dunia yang mengatasnamakan
ingin menerapkan hukum agama, serta banyak lahir kata umpatan dari mulut para
pelantun kalam ilahi yang suci.
Jika hukum secara ambisius mengklaim bahwa ia dapat
mengidentifikasi keimanan, maka semestinya tidak perlu dipaksakan pada semua orang,
karena orang beriman tentu tidak memerlukan daya paksa hukum untuk taat. Namun,
kini sebaliknya hukum justru hendak memaksa semua orang untuk tunduk pada
regulasi yang bersifat massif tersebut. Karena itu, pada dasarnya keputusan
untuk memaksa seluruh orang tanpa pandang bulu adalah tanda yang jelas bahwa
hukum tidak pernah mampu mengidenfikasi keimanan personal.
Ambiguisitas lainnya yang bisa diketahui dari corak
penalaran ini, adalah kekeliruan penerapan logika pengandaian
kemutlakan/kewajiban keberadaan sesuatu. Logika ini bisa dilihat dari contoh
misalnya 2 +…= 2 maka secara logis tanpa harus melihat angka berapa pada bagian
yang belum terisi tersebut, akal sehat manusia pasti mengandaikan keberadaan
angka nol sebagai syarat mutlak bagi keberadaan angka dua sebagai hasil. Logika
kemestian ini terlihat tidak bisa berlaku pada hubungan hukum dan keimanan,
sebab keberadaan hukum tidak memestikan menghasilkan keimanan, dengan demikian
sesuai dengan logika tadi, hukum bukanlah syarat mutlak bagi keimanan.
Berdasarkan penalaran diatas, maka makna “kesadaran
beragama” tidak memiliki similaritas makna dengan penerapan hukum sebagai
sarana yang memiliki daya paksa pada semua orang untuk tunduk pada hukum-hukum
agama, karena penerapan agama dalam hukum pada tahapan tertentu justru
menimbulkan ketimpangan sosial antar ummat agama, bahkan dalam internal
penganut agama itu sendiri, hal mana yang bertentangan dengan tujuan asasi
ummat manusia beragama.
Untuk itu kita mesti menemukan makna lain dari frasa
“beragama dengan kesadaran” yang menempatkan iman sebagai sarana yang mampu
memberikan kedamaian sebagai prasyarat utama yang melindungi kehidupan dan
harkat hidup manusia itu sendiri. Karena sesuai dengan ucapan para ulama, bahwa
“agama diturunkan karena cinta dan kasih Tuhan kepada manusia, karena itu ia
(agama) harus disampaikan dengan cinta”. Cinta tentu saja bukanlah paksaan,
melainkan dorongan nurani yang menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu
yang disenangi kekasih-Nya. Pada tahapan ini seseorang yang melakukan larangan
agama tidak dijadikan sebagai sasaran penghukuman, sehingga seseorang disebut
beriman hanya karena telah menghukum seseorang yang melanggar, melainkan
sebagai seseorang yang sedang haus kasih sayang namun tidak menemukan kekasihNya. Karena bagi
orang yang mengimani bahwa Tuhan adalah sumber penghidupannya, pemberi
wujudnya, maka sejatinya ia juga memiliki kesadaran hidup, bahwa manusia dan
semesta selain dirinya juga sebagai suatu komunitas kehidupan yang meminjam
hidup dari Yang Maha Hidup, karenanya ia juga mencintai kehidupan lainnya.
Dari Akal ke Spiritual
Iman sebagai
elemen penting dari agama harus memiliki landasan yang kokoh, setidaknya pada
tahapan akali manusia. Meskipun pembuktian akali hanya berkedudukan sebagai
pengantar (mukaddimah) bagi kebenaran yang tertinggi yakni Tuhan (Al-Haqq).
Pada bagian sebelumnya kita juga telah mengetahui bahwa hukum hanya dapat
mengatur dan mengorganisir perilaku, namun tidak dapat mengorganisir jiwa. Maka
tahapan primer pembuktian makna Beriman dengan Kesadaran yang benar harus
terlebih dahulu dimulai dengan menjawab pertanyaan “apa unsur eksternal yang
mampu mempengaruhi daya gerak jiwa manusia ke arah yang benar?”
Hukum logika
universal telah memperkenalkan suatu konsepsi kebenaran umum bahwa setiap
keberadan segala sesuatu yang didahului oleh ketiadaan, maka keberadaan
aktualnya tersebut adalah sebagai akibat. Akibat tidak mungkin memiliki wujud
mandiri, karena dalam alam ketiadaannya mustahil bagi segala sesuatu
mengusahakan dirinya agar memiliki wujud. Demikian juga manusia beserta semesta
disekitarnya diidentifikasi sebagai akibat, karena keberadaannya setelah
didahului oleh ketiadaan. Beberapa pandangan telah menolak konsep ini dengan
alasan tidak ada bukti bahwa alam didahului ketiadaan, seluruh realitas semesta
telah ada dengan sendirinya. ketiadaan bukti bahwa semesta “diciptakan” telah
menempatkan gagasan diatas sebagai konsep yang bersifat khayali dan tidak
beradasar.
Namun dengan
pengamatan yang lebih spesifik terhadap kejadian semesta, kita segera
mengetahui bahwa setiap entitas dalam semesta membutuhkan satu sama lain untuk
bisa eksis dan mewujud. Dari berbagai teori kejadian semesta yang berhasil
dihimpun oleh ilmuwan-ilmuwan besar dunia menunjukkan bahwa tidak ada satupun
teori kejadian semesta yang menggambarkan bahwa dari masing masing benda dunia
mewujud dengan sendirinya tanpa membutuhkan dzat lain untuk dapat eksis.
Ilmuwan dunia seperti Enstein, Hoyle, Kant, Laplace, F.R. Moulton dan lainnya
tidak satupun diantara mereka yang memiliki konsep sains mengenai semesta bahwa
masing masing benda memiliki wujud mandiri. Semuanya terbentuk melalui proses
proses alamiah sehingga membentuk aneka ragam benda dan tumbuhan. Namun
diantara berbagai teori sains tersebut, terdapat satu titik yang menjadi muara
pertemuan diantara teori sains mereka, bahwa seluruh proses perwujudan semesta
membutuhkan daya bagi gerak setiap proses perwujudan benda benda tersebut.
Dengan demikian, semesta jelas tidak memiliki wujud mandiri, karena geraknya
membutuhkan sebab, yakni adanya daya (energi) dan setiap sesuatu yang
membutukan pada sebab adalah akibat.
Setelah
pembuktian filosofis diatas, kita mengetahui bahwa manusia juga membutuhkan
sebab bagi seluruh tindakan dan perilakunya tersebut. Adapun sebab yang ada pada manusia tersebut
adalah daya jiwa dan akalnya. Semesta memiliki keteraturan kosmologis
disebabkan adanya hubungan intrinsik antara dirinya dengan Sumber daya utama
yakni Tuhan, sedangkan manusia semestinya juga berjalan demikian, bahwa Tuhan
senantiasa berhubungan dengan manusia melalui Jiwa pemberiannya. Namun hubungan
manusia dan Tuhan tidak serta merta berlangsung sebagaimana hubungan instingtif
yang dimiliki alam, dimana gerak dan kehendak Tuhan sekaligus bermakna gerak
dan kehendaknya alam juga. Dalam peri-kehidupan manusia, Tuhan memberikan dua
kebebasan sekaligus yakni kehendak untuk patuh dan juga sebaliknya, sehingga
keduanya berada dalam alam probabiltas. Dengan demikian kebebasan manusia dalam
menggunakan daya akal dan jiwanya adalah sifat kodrati yang diberikan Tuhan
kepada manusia dan oleh karenanya hubungan antara manusia dan Tuhan juga harus
melalui kebebasan dua elemen tersebut.
Pada Tahapan
ini kita telah memiliki tiga alur gagasan utama dari proses pemaknaan ”Beragama
dengan Kesadaran”, yakni : Pertama,
Manusia Membutuhkan sebab lain bagi gerak dirinya. Kedua, Keterhubungan manusia dengan sumber penggerak utamanya
berlangsung melalui jiwa dan akalnya, dan Ketiga,
Hubungan tersebut harus berlangsung melalui kebebasan jiwa dan akal manusia,
karena kebebasan adalah sifat kodrati yang diberikan Tuhan sehingga mustahil
Tuhan berhubungan dengan Makhluk diluar kodrat pemberiannya. Dari ketiga alur
gagasan tersebut, meski manusia memiliki akal dan jiwa sebagai modal utama dalam
menyerap informasi serta merancang peradaban, namun kualitas kognisi (akal)
belum mampu memastikan terwujudnya dunia yang damai serta menempatkan
kemanusiaan pada poros utama peradaban.
Akal tidak bisa menyisihkan sifat ego, keserakahan dan keinginan untuk
mengeksplorasi atau mendominasi tanpa batas bukan hanya terhadap alam namun
juga antar sesama manusia. Sedangkan disisi lain, kualitas peradaban yang benar
tidak hanya ditentukan seberapa banyak kognisi manusia mampu memproduksi
sejumlah pengetahuan untuk meneguhkan eksistensi sekelompok orang, namun
bagaimana mengkreasi suatu peradaban yang mampu menghargai kemamanusiaan secara
universal. Rangkaian sejarah kemajuan teknologi dunia tidak memiliki makna
apapun jika dunia dipenuhi oleh kekacauan, peperangan dan diskriminasi hak
kemanusiaan, karena Pengetahuan tidak mampu melindungi manusia sebagai produsen
pengetahuan itu sendiri.
Karenanya
meskipun akal adalah salah satu potensi yang sangat penting dalam diri manusia
namun ia bukanlah unsur superior dalam diri manusia. Kebenaran ini dapat ditelusuri
dengan mengetahui objek daripada akal
yang sesungguhnya. Dalam prinsip-prinsip dasar nalar sains, akal memainkan
sejumlah peran terutama dalam menentapkan rangkaian hukum-hukum sains seperti
halnya hukum kausalitas, kaidah-kaidah logika matematis, serta berbagai
postulat-postulat ilmiah lainnya. Namun penyandaran seluruh hukum hukum
tersebut sesungguhnya tidak pernah ditemukan diluar dunia idea. Misalnya
tentang prinsip kausalitas, konsep satuan, himpunan, deretan angka numerik,
satuan panjang, satuan luas, ketinggian, kedalaman dan lainnya. Seluruh
hukum-hukum dan satuan tersebut pada dasarnya tidak ada secara real dalam dunia materi, ia hanya lahir
dari pengorganisian idea secara sistematis sehingga dapat diterapkan pada dunia
materi. Kita tidak dapat menunjukkan yang mana yang disebut “Meter” dalam
sepotong kayu, atau mana yang disebut “Tinggi “ pada sebuah gunung. Satuan dan
Hukum tersebut hanya bisa diterapkan pada materi namun tidak ada wujud
materialnya, disebabkan satuan dan hukum tersebut hanya ada dalam dunia idea namun disimbolkan dan dilekatkan
pada materi agar bisa dipahami. Dengan demikian objek utama daripada akal
bukanlah materi atau akal itu sendiri, melainkan Jiwa tempat melekatnya akal.
Akal hanyalah karakter dari pada Jiwa, yakni jiwa yang berpikir.
Karena Jiwa
adalah tempat melekatnya akal, maka Jiwa menduduki posisi primer dalam diri
manusia. Kualitas jiwa menentukan intensitas akal, meskipun tidak selamanya
intensitas ini berwujud pengetahuan ilmiah, namun manifestasinya melalui adanya
dorongan yang kuat pada diri setiap insani untuk memelihara keteraturan
kosmologis antar sesama manusia dan
semesta secara keseluruhan. Karena manusia pada hakikatnya adalah bagian dari
kesatuan kosmologis dengan alam, namun dengan esensi yang terpisah satu sama
lainnya. Pada tahapan inilah kualitas akal dan jiwa harus mendapat penjelasan
yang proporsional mengenai bagaimana hubungan saling mempengaruhi diantara
keduanya dan faktor apa saja yang mempengaruhi perbaikan kualitas jiwa seorang
insan.
Jiwa internal
manusia jelas tidak mampu mempengaruhi dirinya sendiri agar menjadi baik,
karena jika masing masing mereka dinilai memiliki kemampuan menjadikan diri
baik dan sempurna, maka tidak ada satupun yang dapat diidentifikasi sebagai
kebaikan murni karena seluruhnya berada dalam keadaan relatif. Karenanya jiwa
internal manusia harus memiliki keterhubungan dengan jiwa asasinya yakni Daya
Penggerak Utama (‘illatul-ilal) yang
menjadi jiwa dasar bagi seluruh gerak kosmik semesta (Tuhan). Tuhan dalam
berbagai varian sebutannya juga sering dikenal dengan kata “Rabb”
atau “Rabbul ‘Alamin” artinya
Pengatur, raja atau pemilik semesta raya. Manifestasi dari keterhubungan jiwa
insan dan Rabb-nya akan melahirkan pengalaman dan konsepsi mengenai ketunggalan
asal pencipta pada diri manusia dan secara langsung berimbas pada perwujudan
keharmonisan manusia dengan Tuhan dan unsure semesta lainnya.
Merujuk pada
paparan diatas, maka “beragama dengan kesadaran” berlangsung pada kesadaran bahwa kita manusia tidak memiliki kapasitas
untuk memperbaiki diri dan oleh karenanya membutuhkan sebab lain yang lebih
tinggi sebagai sumber pendidik (rabbaniyah).
Atas dasar itu juga, fungsi agama harus mampu mengantarkan manusia pada
keterhubungan jiwa insaniyahnya dengan daya penggerak utama (Tuhan) dan
sekaligus sebab bagi segala akibat gerak kosmik. Namun pencapaian konsepsi
“beragama dengan kesadaran” seperti ini tidak
bisa tercapai tanpa adanya kebebasan manusia dalam mencapai realitas
eksternal yang menjadi penggerak jiwa kesadaran manusia tersebut.